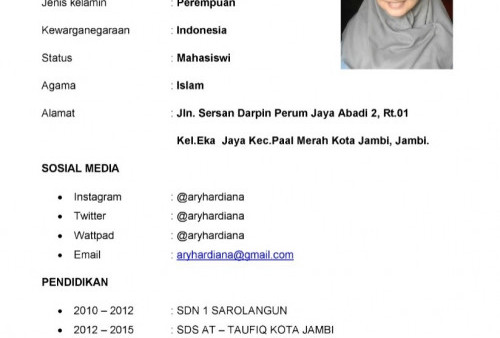Bagian 20: “Jangan Pergi, Bahagia”

Ari Hardianah Harahap--
“Kamu tau mengapa duka ditinggalkan selalu menyakitkan? Sebab menyesal apapun kita, dan sekeras apapun kita, tidak ada yang berubah, ia telah tiada dan kita berkubang dalam penyeselan tanpa tepi, tanpa akhir, terus hingga kita turut tiada dalam luka.”
>>>***<<<
Sandi pernah bilang, satu satunya duka yang paling ia benci menjadi manusia adalah tentang kehilangan, sebab tak ada lagi raga yang mampu ia peluk, tak ada lagi suara yang akan ia dengar, taka da lagi tawa yang akan ia bagi, dan tak ada tangis lagi yang harus ia tenangi. Sandi akan kembali menjadi manusia yang sendiri, yang harinya sepi, yang akan terus menepi dari sisi manapun ia berdiri. Dan saat pertama kali, Sandi mengenal Bian sebagai adik, memberinya sebuah cerita tentang hangatnya keluarga, mengizinkannya untuk menyapa sang Bunda, menjadi saudara yang berbagi dalam suka duka, maka tak ada lagi yang mampu menandingi bahagia Sandi kini. Tapi, semesta selalu punya rencana yang tak pernah terduga, selalu saja memberi kejutan yang tiba – tiba, hingga Sandi hanya mampu tergugu tanpa kata, menangisi hal yang tak ingin ia rasakan lagi, sebuah duka tentang kehilangan, dan sebuah sakit saat kembali ditinggalkan.
“Lo jangan nangis dong goblok, malu sama badan, udah gede juga!” Kesal Bian yang terbaring di ranjang rumah sakit dengan wajah pucat, bibirnya tak berhenti mengumpati Sandi yang terus saja mengiba layaknya Bian akan mati nanti, namun matanya tak mampu berbohong, berkaca- kaca dan turut menahan air mata yang ingin tumpah. Tidak ada satupun perkataan Bian yang mampu Sandi gubris, hatinya terlanjur kecewa, kepada siapa saja, dirinya, Bian, dan naifnya ia sebagai manusia.
“Sandi..” Panggil Bian lirih, “tolong jangan nangis, kasian Bunda diluar, gue nggak kenapa – kenapa, gitu juga nanti, kita bakal tetap main sama – sama, kan katanya lo mau anak gue sama anak lo sahabatan kayak kita juga, jadi please…” Kali ini Bian memohon air matanya tumpah, tentang mengapa harus ia yang memberi luka, sebuah permohanan sedari dulu yang ia tuju pada tuhan, jangan ada tangis untuknya, nyatanya tak dikabulkan. Ironinya ia sebagai manusia, yang masih seenaknya padahal sebentar lagi adalah waktunya, sebagai sebuah jasad tak berdaya.
“Lo kenapa nggak pernah bilang?” Lirih Sandi, kepalanya tertunduk dengan air mata, menatap lengan sang sahabat yang ditempeli dengan banyaknya alat, yang kurusnya kini tak pernah Sandi bayangkan, lengan yang biasa menyapa dan memeluknya dalam keadaan apa saja, menawarkan sebuah luka dan juga rasa kini terkulai lemah.
“Sandi jangan nangis…” Mohon Bian, kali ini ia biarkan isaknya terdengar, ia biarkan lukanya terbuka, “Jangan nangis, gue takut kalo nanti gue beneren nggak bisa meluk bunda lagi, gue takut kalo gue nggak bisa ganggu lo lagi, gue takut sandi…” Tangis Bian histeris.
“Gue takut kalo nantinya gue nggak bisa liat kalian lagi, gue masih mau mimpi bareng lo, Jingan dan Jinan. Gue takut sendirian, gue takut untuk segala hal nanti, gue takut sandi….Gue takut.” Jerit Bian dengan nada pilunya, Sandi memeluknya, kedunya berbagi luka dan sesak yang telah lama mereka abaikan, diantara lukanya, Sandi paksakan tawanya terlontar, “Lo masih harus sukses bareng sama gue, kita masih harus adu mekanik pesta pernikahan kita, kita masih….kita masih harus ada sampai tua dan liat anak cucu kita main sama – sama….lo percaya kan Yan?” Ujar Sandi, nadanya getir, bahka ia meragu dengan kenyataan yang terlontar dari bibirnya.
“San, gue capek, titip bunda nanti…”
“Jangan dulu…” Tahan Sandi, tubuhnta gemetar memeluk Sandi lebih erat, “Lo bahkan belum bilang suka sama cewe idaman lo, minimal dia harus tau kalo dia dicintai sama orang sekeren lo. Kita juga belum kasih surprise buat ulangtahun bunda, lo janji sama gue buat main ps bareng, lo janji sama jingan buat traktir dia cilor, lo janji sama Jinan buat hadiah bukunya…masih banyak yang harus lo lakuin Yan…” Sandi tergugu, ia remat sekuat tenaga raga yang kini terasa sangat berat di peluknya.
“yang bahagia abang…” Bian tahu, selama waktu yang ia jalani bersama Sandi, sahabatnya itu berperan lebih dari suadara untuknya, bahkan Bian peka tentang Sandi yang selalu ingin diakui sebagai abangnya, hanya saja menjahili Sandi selalu menyenangkan untuk Bian, lagipula sekarang sudah saatnya, Bunda sudah mengakui Sandi, dan Bian menyanyangi Sandi sebagai saudara, Sandi juga lebih tua setengah tahun dibanding dirinya, sekarang Bian mampu memanggil Sandi dengan sebuatan yang selalu diidamkannya itu.
“Bian….” Lirih Sandi, bisikan Bian nyaris tak terdengar, hingga Sandi benar mampu merasa bahwa Bian menopang seluruh tubuhnya pada Sandi, tak ada lagi tangis yang mengurai selain tangis Sandi, tak ada lagi kata, selain getirnya Sandi, ia pergi meninggalkan Sandi sendiri, dengan duka dan luka yang mendalam….
“Bian..jangan pergi, aku nggak bisa jadi abang kalo nggak ada adek,” (bersambung)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: