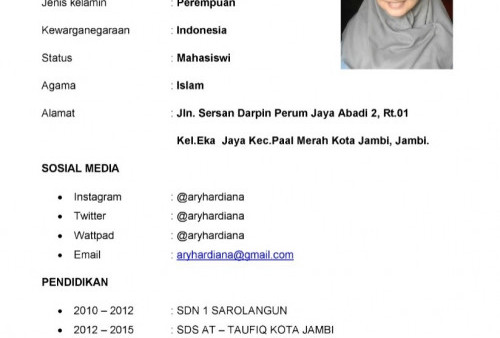Bagian 11: “Manusia Nano – Nano”

Ari Hardianah Harahap--
“Jadilah manusia yang luar biasa tapi jadilah dengan cara yang paling sederhana”
-Sandi
>>>***<<<

yamaha--
Ini sudah dua tahun lalu, sejak terkahir kali Bian menginjakkan kakinya di Pasar Raya, tempat yang menjadi saksi ia yang terus mengeluh pada setiap tanah basah yang tertempel di kakinya. Tempat dimana, suka tak ia suka terus menyunggingkan senyumnya untuk para penjual, tempat dimana ia yang sangat malas mengeluarkan suaranya, dipaksa untuk terus berkata tidak di sepanjan jalan menuju pulang. Berbeda dengan sahabatnya, Sandi. Yang dengan semangat menyapa semua pedagang, yang tak mempermasalahkan apapun yang lengket pada tapak sepatunya, atau tentang bau menyengat yang terus menusuk hidung mereka. Kunjungan Bian kali ini berbeda, tidak tau mengapa ia putuskan langkah kakinya kemari, sendiri. Padahal, biasanya akan selalu ada Sandi di sisinya, tapi kali ini ia biarkan dirinya mencari metaforanya sendiri di tempat dengan berbagai macam manusia.
“Bang, Bang, beli kacang nggak?” Tepat lima meter berjalan dari penurunan angkot, Bian harus mati – matian menahan emosinya saat tangan kecil anak laki – laki itu menyentuh kameja moccanya, noda hitam tertinggal disana, jelas tapak tangan bocah laki – laki tersebut, Bian menggerang kesal, “Enggak! Pergi sana!” Kesal Bian, wajah bocah laki – laki itu tampak bersalah, matanya berkaca – kaca namun tak Bian pedulikan sedikitpun, sibuk mengibasi noda kotor dibajunya.
“Maaf ya bang, tangan saya kotor.” Ujar Bocah tersebut yang membuat Bian tersentak kaget, maaf yang begitu tulus terlontar, bahkan saat Bian telah memaki dan mengusirnya, “besok saya bakal cuci tangan terus, biar nggak ada bajunya yang kotor lagi.” Bian semakin tersentil jauh, mengapa Bian harus merasa sangat bersalah, padahal perkataan dan sikapnya tidak sepenuh salah. Bocah tersebut meninggalkan Bian, menepi bersama teman – temannya, tampak membuat lingkaran dan berdiskusi kecil – kecilan. Bian tak lagi ambil pusing, ia teruskan perjalanannya. Dan lagi – lagi, ada saja hal yang terus memancing emosinya.
“Aduh dek maaf ya saya nggak sengaja,” Wanita paruh baya tersebut menatapnya khawatir, memerika kakinya dengan seksama sebab tertimpa keranjang sayur, tergopoh – gopoh ia berlari ke toko terdekat, membeli es batu dan memberikannya pada Bian, “Maaf ya nak ibu benar – benar nggak sengaja, kalo bengkak sini ibu kompres pake es nak.” Ujar Wanita tersebut menggapai kaki Bian yang segera Bian tahan. Walau tersenyum paksa, dan terasa sakit kakinya, Bian juga sama tidak teganya, “Gapapa bu, duluan saja,” Ujar Bian, terburu – buru ia tinggalkan wanita tersebut sebab air yang tadinya rintik, kini ia rasakan semakin deras. Sejak tadi awan memang gelap, namun Bian abaikan sebab rasa penasarannya tentang pasar kumuh ini, atau tepatnya tentang mengapa sahabatnya seseorang seperti Sandi, mampu menghabiskan waktunya seharian disini, bahkan tempat ini jauh dari kata layak untuk dijadikan wisata.
Hujan benar – benar datang dengan derasnya, menerabas segala manusia di bawahnya. Bian berlari kecil, berteduh diantara paying – paying penjual es, rata rata dari mereka tampak suram sebab hari ini kemungkinan dagangan mereka tidak akan laku sama sekali. Namun, Bian temukan satu yang terus tersenyum sedari tadi menatap hujan.
“Hujan bang?” Tanya Bian, yang dibalas anggukan semangat oleh si Abang penjual Es tebu tersebut. Rautnya sumringah, tidak ada sama sekali panik atau pun khawatir di raut wajahnya.
“Es dek?” Tawar Abang itu yang ditolak gelengan kepala oleh Bian, yang dibalas dengan senyuman secerah matahari pagi, “Kalo hujan gini bakal laku nggak bang es-nya?” Tanya Bian iseng, Abang tersebut nampak berpikir, mengangkat kedua bahunya. Kemudian tersenyum dengan amat bahagianya.
“Dulu, saya sama khawatirnya dengan mereka,” Ujar abang penjual es tersebut tiba – tiba, menunjuk sekumpulan pedangan es lainnya yang berwajah masam. “Tapi, ada satu pemuda yang datang ke saya, hari itu nggak ada sama sekali yang beli jualan saya, dia satu – satunya, hujan juga masih sama derasnya, dia bilang ke saya, saya beli es abang, supaya abang tahu bahwa tuhan nggak pernah lupa sama hambanya, dia emang cuma beli satu tapi dia menyelamatkan nyawa saya setiap harinya untuk sesuap nasi.” Bian dapat merasakan rasa haru dari nada bicara abang tersebut, hingga Bian merasa dipanggil oleh sekumpulan bocah yang kehujanan.
“Abang – abang, ini baju baru biar baju abang nggak kotor lagi,” Anak tersebut berlari tertawa bersama seorang pemuda yang seumuran dengannya, yang sangat ia kenal baik, seseorang yang terus ia anggap saudaranya, seseorang yang terus menjahilinya hingga Bundanya pun seolah menjadikan pemuda tersebut atensi sesungguhnya. Genggaman keduanya erat, menerobos hujan. Tertawa diantara ramainya manusia yang menonton mereka.
“Abang, maaf ya bajunya tadi kotor gara gara Adnan,” Bocah laki laki yang bernama Adnan tersebut, tersenyum luwes, ia berikan plastikan yang sudah setengah basah itu pada Bian. Bian terima denga senyum, “Maaf abang ngebentak kamu tadi.” Ujar Bian tulus yang dibalas dengan cekikan, “Adnan juga salah tadi.” Balas Adnan yang dihadiahi jempol oleh pemuda yang dibawa bersamanya.
“Hari ini kayanya saya harus beli es abang deh,” Pemuda yang Adnan bawa bersamanya itu mengerling jahil yang dibalas tawa serempak oleh kedunya, “makasih ya,” Balas abang tersebut yang diangguki oleh pemuda itu.
Diantara sisa sisa hujan, pikiranku melanglang buana, hingga tepukan bahu itu menyadarkanku, pemuda itu Sandi, yang kupertanyakaan eksistensinya beberap jam yang lalu. Layaknya benang yang kusut, pemuda itu tertawa, “Tau kenapa harus disini?” Tanya Sandi tiba – tiba yang Bian balas dengan gelengan kepala.
“Supaya kita tahu, merendah itu sebuah keharusan dan meninggi itu sebuah kewajaran, boleh dilakukan tapi tidak selalu,” Sandi tersenyum, “Kita jadi manusia yang biasa aja, selayaknya sampai kita harus berpisah dengan semesta. Untuk jadi manusia luar biasa kita nggak selalu butuh eksistensi yang banyak, dengan hal yang paling sederhana aja kamu bisa jadi manusia yang paling berharga.”
Hari itu, Bian hanya mengangguk, entah mengapa rasanya menjadi manusia itu terlalu nano – nano untuknya. (bersambung)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: